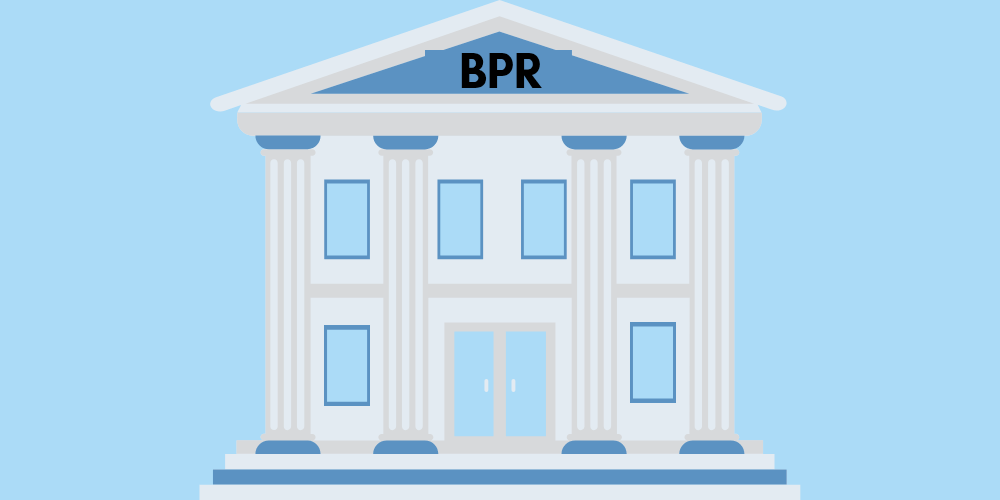“Bahaya globalisasi adalah bukan bahwa manusia mengingkari eksistensi Tuhan, atau bahwa manusia meninggalkan ikatan-ikatan religius mereka. Bahaya globalisasi tepatnya bahwa manusia tidak lagi mendapatkan banyak peran untuk Tuhan dalam kehidupan mereka, maka peranan Tuhan dikecilkan dan dibuat tak berarti dalam kehidupan mereka. Bahaya globalisasi mendorong manusia untuk berpikir tentang dunia dalam batas-batas ateisme dan materialisme walaupun mereka beragama Oliver Leaman (terj. Ali Yahya, 2005: xxx).
Sebuah hasil analisa tajam seorang ilmuan di atas, tidak lagi hanya bekerja dalam ruang teori belaka, tidak lagi berada pada menggedor pintu, melainkan bahaya itu telah melangkah maju ke dalam rumah, makin masiv manakala politik dipraktikan dengan perilaku kekuasaan oriented, yang mengandaikan dunia ini milik mereka.
Satu sisi, peran Tuhan hanya digerakkan di atas panggung untuk mencari dukungan belaka dan keuntungan pribadi, kelompoknya semata. Di sisi lain, rakyat hanya dijadikan pijakan atau tumbal di atas kemiskinan dan pembodohan.
Praktik kekuasaan semacam itu memanfaatkan rakyat persis seperti kata Gustave Le Bon, dalam psychologi massa. Massa itu bodoh, mudah diprovokasi, bersifat realistis, atau singkatnya: irrasional (F.Budi H, 2005: 67).
Seperti dalam teori John Lock, menjelaskan dalam argumentasinya bahwa semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, merupakan hak mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Untuk itu, demi menghindari ketidakpastian hidup, dalam teori kontrak sosial atau ikatan sukarela maka menyerahkannya pada negara.
LIhat juga Zaman Serba Boleh
Namun, apabila penguasa negara melanggar hak-hak yang bersifat kodrarti itu maka kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu (Scott Davidson, 1994: 37-38).
Penghormatan atas hak-hak kehidupan, kebebasan dan harta yang secara inheren melekat pada diri setiap manusia merupakan implementasi keadilan dan tanggung jawab itu ada pada negara.
Emmanuel Kant, apa yang disebutnya dalam merepresentasikan kepentingan umum pilihan utamanya adalah keadilan. Hukum ada dan digunakan dengan tujuan mewujudkan keadilan. Hukum dari kata “ius” memiliki dua arti. *Ius* dalam arti subyektif sebagai hak (rights), *ius* dalam arti obyektif, yaitu hukum.
Kedua arti kata itu menunjukan bersifat integratif, tidak terpisah. Namun dalam semua hal baik dalam praktik politik, ekonomi, khususnya hukum, akan bekerja dengan baik apabila manusia di belakang yang menjalankan dan menegakkan hukum itu juga orang-orang baik.
LIhat juga Sungguhkah Politik Uang mau Diberantas? Ini Ancaman Pidana Politik Uang di Pemilu 2024
Filosof Teverne, menangkap gejala tidak bekerjanya hukum dengan baik itu lantaran manusia di belakang hukum itu tidak baik. Kalimat populer yang diucapkannya, “berikan saya polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, seburuk apapun undang-undang akan melahirkan keputusan yang baik”.
Kebaikan adalah nilai-nilai ke-Tuhan-an yang diperintahkan, itu demi kemasalahatan kehidupan manusia itu sendiri. Namun nilai-nilai itu dalam praktiknya tidak dijalankan, maka yang terjadi seperti dalam sebuah penggalan sajaknya Remy Sylado. “Keadilan adalah milik orang kuat, dan aku terpaksa menerima kata adil”.
Kesejahteraan yang bersifat empirik sering lebih dimanipulasi dengan angka statistik, lalu disulap dengan pembagian sembako alakadarnya, atau menggelar pasar murah sepintas. Sedangkan keadilan dalam wilayah non-empirik, berorientasi pada apa yang harus didapat yang menjadi haknya dan bersifat parmanen.
Kekuasaan yang dibangun atas dasar rasionalitas dengan fondasinya kultur feodal sekadar menargetkan urusan tujuan di satu pihak, sedangkan di pihak lain, menafikkan nilai-nilai (values) pada keta’atan pada moralitas, yang dalam penjelasan Marcuse, one-dementional man, melukiskan bagaimana proses rasionalisasi masyarakat bermuara ke dalam sebuah tragedi besar.
Mendewakan rasionalitas yang semula dianggap memberi otonomi dan kebebasan, manusia dewasa justru terperangkap ke dalam jaringan birokrasi yang impersonal dan kehilangan makna serta aspirasinya sebagai makhluk bermartabat (F.Budi H, 1993: 73-74).
Sikap pragmatisme semacam itu mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar dan orientasinya pada tujuan kepentingan privat, kelompok sepaham, yang dalam pandangan Marcuse di atas, terperangkap ke dalam jaringan birokrasi impersonal. Bahayanya Kecenderungan semacam itu apa yang oleh Arendt sebagai *der Mensch*, merujuk proyek homogenisasi, uniformisasi dan purifikasi rezim-rezim totaliterian (F.Budi H, 2005: 22).
Tuhan mengajarkan perbedaan laki-laki, perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal dan saling menghormati (QS. Alhujarat: 13). Dengan perkataan lain, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, yang dalam perspektif politik yang demokratis, pengakuan manusia sebagai subyek (souvereign) harus diletakkan atau diposisikan secara equal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya kesadaran itu menjadi bagian integral dengan tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupannya secara adil.
Wallahu’alam bisshowaab.