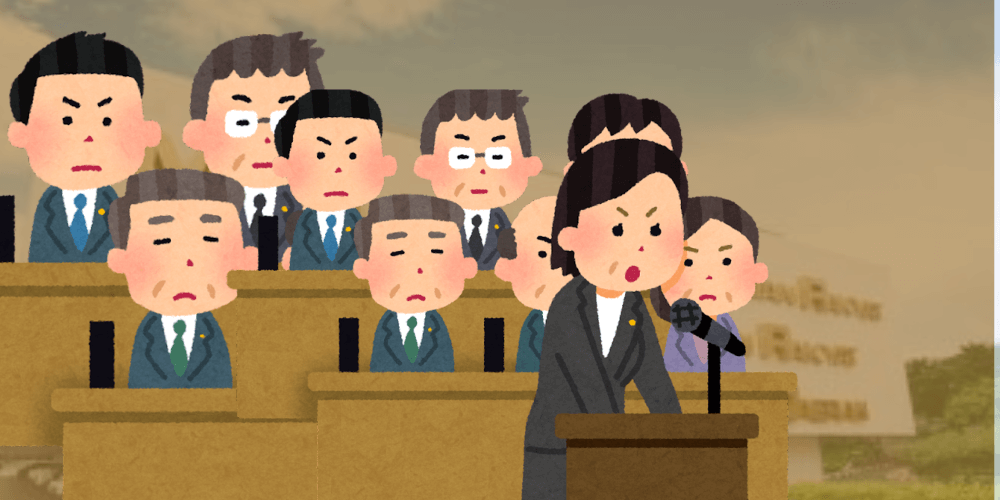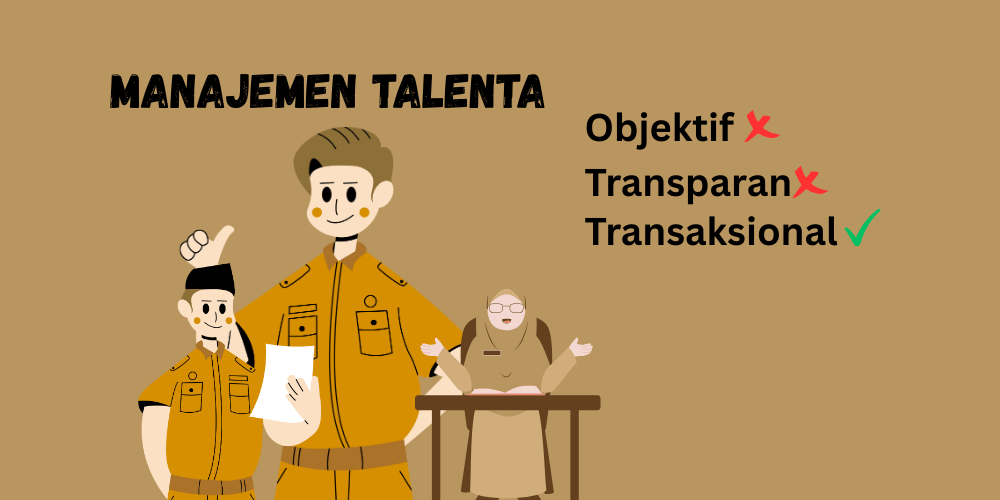Pilkada 2024, Pertaruhan Harga Diri Partai Politik


Selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 memberikan gambaran kepada kita tentang partai politik atau parpol apa saja yang dapat merebut suara rakyat pada pemungutan suara, khususnya pada pemilihan anggota DPR dan DPRD, sehingga parpol tersebut dapat menempatkan kadernya di lembaga lesgilatif baik pusat maupun daerah.
Sebanyak delapan parpol berhak mendapatkan kursi di DPR RI. Sementara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota parpol peraih kursinya beragam, namun delapan parpol peraih kursi DPRD dipastikan mendapat jatah.
Saat ini para elit parpol sudah kembali disibukkan persiapan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak, 27 November 2024, baik untuk gubernur maupun bupati/walikota. Jika di Pemilu 2024 parpol mampu dan mau menempatkan kader-kader mereka di legislatif, apakah di Pilkada, parpol akan mampu dan mau mengusung kader mereka sendiri untuk merebut kursi kepala daerah? Atau mereka cukup ‘menyewakan’ atau bahkan ‘menjual’ murah kepada orang yang bukan kader parpol mereka, pelancong politik, dan/atau wakil oligarki lokal.
Lihat juga Hukum dan Kekuasaan
Tidak aneh dan sangat nyata. Dalam banyak perhelatan Pilkada, perilaku elit parpol sangat menunjukkan ketidakpercayaan pada kemampuan kadernya sediri untuk bisa memenangi kompetisi. Sikap self-doubt ini dilatarbelakangi beberapa faktor seperti popularitas dan elektablitas kader internal yang diaggap tidak memiliki kapasitas, serta tentu saja ‘isi tas’ yang dinilai tidak pas.
Motivasi terselubungnya, kepentingan pragmatis bersifat materil ekonomis baik berupa uang tunai tanda mahar atau berupa permufakatan janji bayar budi jangka panjang. Ini lebih menggiurkan, ketimbang bercapek-capek kompetisi dengan kemungkinan tak menang. Begitu kira kira cara pikir elite parpol saat dihadapakan pilihan memberdayakan kemampuan kader parpolnya dengan konsekuensi tak menang, atau ikut menang dengan kader lain parpol sambil dapat mahar.
Parahnya lagi, orang eksternal yang diusung dan didukung tidak memiliki track record baik, dia pernah terkena isu korupsi, bahkan keluarganya pengusaha atau bekas pemimpin daerah yang koruspi, dia juga tidak populer populer amat dengan elektabilitas alakadarnya pula. Tak apalah asal punya duit, begitu rumusnya.
Sentralisasi Pencalonan
Perilaku elite parpol daerah yang tak percaya diri dalam urusan pengusungan calaon pada Pilkada makin parah sejak berlakunya sentralisasi proses pencalonan atau pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah menjadi Undang-undag Nomor 10 Tahun 2016, pendaftaran bakal calon kepala daerah wajib menyertakan surat keputusan persetujuan pengurus partai politik tingkat pusat (pasal 42 ayat 4 dan 5).
Ketentuan ini jelas membonsai otoritas pengurus parpol di daerah sekaligus membuat ‘mahal’ proses pencalonan di tingkat partai politik akibat tahap berjenjang mulai pengurus daerah sampai mendapatkan persetujuan pengurus pusat.
Tahapan pencalonan di internal partai ini, tentu membuat para bakal calon harap harap cemas, meski berasal dari internal parpol. Lolos di pengurus daerah, belum tentu ddisetujui pengurus pusat. Restu pusat adalah kunci.
Di sinilah potensi transkasional ada dan semakin memarjinalkan kader potensial namun miskin. Ini jauh berbeda dengan saat masih berlakunya rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahan 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentagn Pemerintahan Daerah. Kala itu, untuk mendaftarkan bakal pasangan calon cukup menyertakan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
Ambang Batas Syarat Pencalonan
Sementar itu, ambang batas atau threshold jumlah kursi atau jumlah suara sebagai syarat pencalonan dalam Pilkada yang tinggi juga menjadi factor peningkat keraguan pada elite lokal parpol, yang akibat syarat itu acapkali menyerah pada figur yang muncul dari parpol koalisi atau yag disepakati gabungan partai pengusung. Itu karena parpolnya tidak mampu memenuhi ambang batas jumlah kursi sebagai syarat pencalonan.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, ambang batas jumlah kursi untuk bisa mengusung pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (pasal 40, UU 10/2016). Dengan sistem multipartai seperti sekarang, ambang batas ini bukan hal mudah. Koalisi adalah solusi.
Saat rezim Undang-undang Pemda, ambang batas pencalonan Pilkada hanya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ambang batas ini lebih rasional bagi parpol.
Politik Transaksional
Tak dipungkiri, sentralisasi dan ambang batas pencalonan memunculkan potensi politik transaksional yang tinggi di partai politik saat proses menuju pengusungan dan pemberian dukungan bakal pasangan calon. Asumsinya, transaksional bisa terjadi di leval mana saja. Kalau mau mulus, terjadi di daerah dan pusat, kalau mau potong kompas langsung main pusat. Ah sulit pula dibuktikan.
Praktik traksaksional ini adalah silent killer bagi kader dan efektif mendemotivasi orang-orang berkualitas dalam parpol untuk muncul sebagai calon kepala daerah.
Wal hasil, ogah susah mencari koalisi parpol yang belum tentu direstui pengurus pusat, dan tak sikap Inferiority complex yang menjangkiti para kader menjadi lengkaplah keterpurukan mental kader parpol di hadapan figur yang sudah mendapat restu langitan.
Transaksional politik ini juga menjadi ranah persaingan bagi para aktor parpol, prinsipnya, ogah rugi. Sehingga, bagi parpol-parpol yang kadung ‘lemah syahwat’ semacam menemukan kejantanannya ketika tawar menawar politik jelang pengusungan pasagan calon terjadi.
Harga Diri Parpol
Stanley Coopersmith, seorang ahsli kepribadian, menyatakan bahwa harga diri adalah penilaian personal terhadap diri sendiri yang mencerminkan seberapa besar dirinya mampu, berarti, sukses dan dihargai yang diekspresikan melalui sikapnya sendiri.
Dia mengemukakan ada empat aspek yang terkandung dalam harga diri yaitu, power (kekuasaan) dalam arti kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah laku orang lain. Significance (keberartian) yaitu adanya kepedulian, perhatian dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Virtue (kebajikan) yaitu ketaatan atau mengikuti standar moral dan etika, dan Competence (kemampuan) dalam arti sukses menuruti tuntutan prestasi.
Hari hari ini, parpol di daerah sudah kehilangan otoritas (poer/kekuasaan) penuhnya dalam mengusung calon kepala daerah. Partai politik juga tidak lagi dianggap sebagai laboratorium ideologi namun hanya dipandang sebagai ‘kendaraan’ oleh pihak atau orang lain yang punya minta politik untuk mencalonkan diri pada Pilkada, bagi yang punya minat ini parpol hanya elemen taktis belaka tak ada Significance parpol dengan individunya. Aspek Virtue (kebajikan) yang mensyaratkan pengamalan dan ketaatan pada standar moral dan etika juga tak dimiliki jika praktik traksaksional terjadi dalam pengusungan pasangan calon. Terakhir, parpol yang hanya mendukung figur lain jelas tak memenuhi aspek Competence (kemampuan), karena kader-kadernya tidak berhasil memenuhi tuntutan prestasi untuk setidaknya mejadi calon kepala daerah dari parpolnya. Jika kesemua aspek harga diri tak dimiliki partai politik, lalu dengan asalan apa partai politik merasa masih merasa berhak meminta suara kami, suara rakyat?