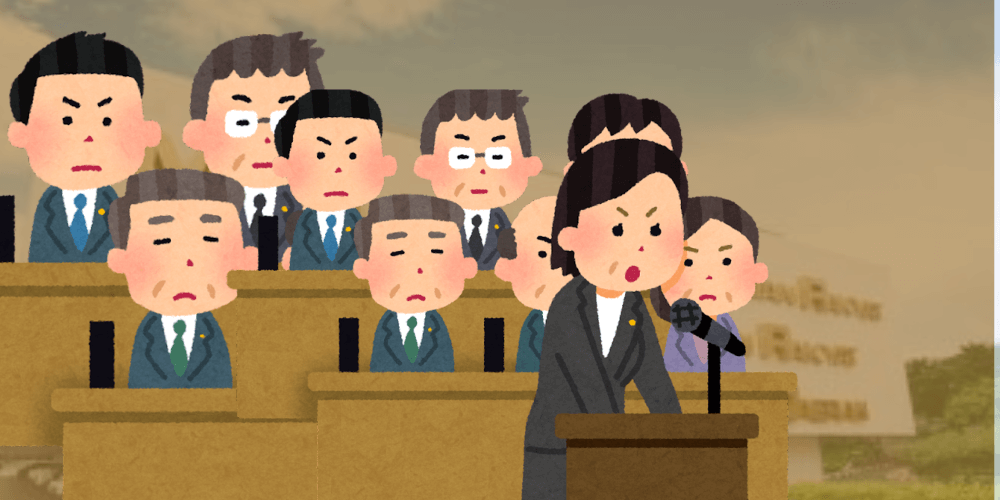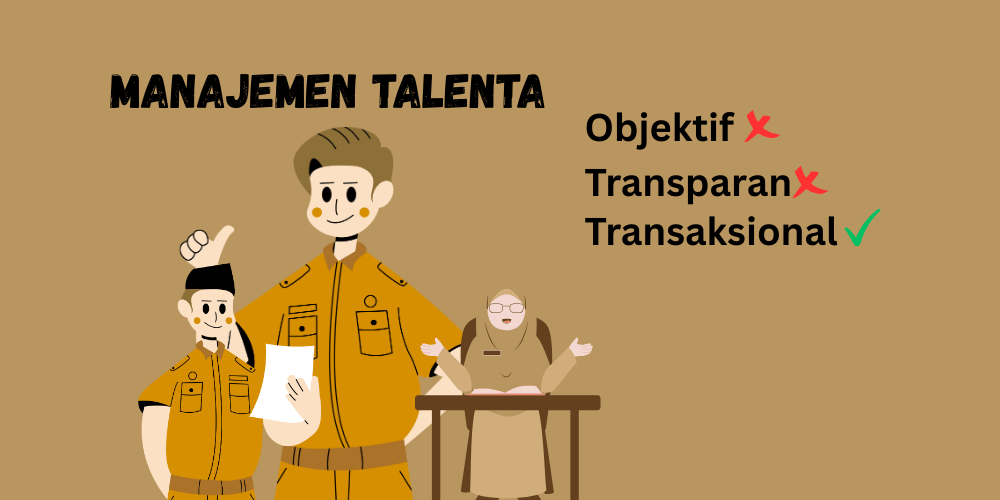Mengintip Seleksi Caleg

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, proses pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota akan dimulai tanggal 24 April 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. Namun, jauh hari sebelum itu, pada pertengahan bulan September 2022, sejumlah parpol nampak sudah merancang pola rekrutmen para caleg. Bahkan sebagian parpol sudah membuka pendaftaran caleg di kantor partai masing-masing sesuai tingkatan.
Mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 1, menyatakan, parpol melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Ayat 2 menuturkan, rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 ayat 2 UU 2/2011 ini layak diperdebatkan. Secara harfiah, rekrutmen yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, hanya dilakukan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Apakah kemudian dapat dikatakan secara sederhana, bahwa rekrutmen anggota parpol dan bakal calon anggota DPR dan DPRD, tidak dilakukan secara demokratis dan tertutup. Mungin tidak bisa diartikan demikian. Parpol tentu memiliki pola kaderisiasi tersendiri untuk hal itu.
Penulis pernah secara khusus menelisik dan mempelajari AD ART parpol yang kini memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019. Terlihat bagaimana pola pengaturan kerja partai yang bersifat sentralistik karena hanya ditentukan oleh satu orang yang diberi kewenangan sangat istimewa. Satu orang itu bahkan dapat menentukan siapa kandidat yang bakal diusung sebagai kepala daerah di level gubernur bahkan bupati dan walikota. Mereka memiliki sebutan nama berbeda antar parpol.
Tahapan rekrutmen caleg oleh parpol adalah bukan salah satu dari tahapan pemilu. Karena itu KPU maupun Bawaslu sama sekali tidak bisa mengakses pola yang dilakukan parpol tertentu dalam menseleksi caleg. KPU hanya menerima daftar nama caleg dari parpol disertai persyaratan administrasinya. Bagimana si Fulan ditempatkan menjadi caleg nomor urut 1 pada sebuah Dapil, sementara si Mawar misalkan menjadi caleg nomor urut 3, KPU sama sekali tidak bisa menjelaskan karena itu sepenuhnya menjadi kewenangan parpol.
Dengan sistem proporsional terbuka, parpol diharuskan menampilkan para caleg. Ironisnya, masyarakat tidak dibekali informasi yang cukup mengenai profil si caleg. Pemilih harusnya diberikan akses yang memadai untuk mengetahui mengapa si caleg tersebut mendapat nomor urut tertentu, apa pertimbangan yang bersangkutan ditetapkan sebagai caleg, apa benefit rakyat jika caleg dimaksud memenangkan pertarungan, dan lain sebagainya.
Kata demokratis dan terbuka tersebut harus dimaknai bahwa masyarakat harus diberikan akses. Berikutnya, kualifikasi si caleg dimaksud juga harus terukur secara jelas. Misalkan tentang jejak rekam yang bersangkutan. Bagi petahana contohnya. Ketika dia dicalonkan kembali, maka rakyat harus tahu persis apa dan bagaimana kiprahnya selama 5 tahun menjabat.
Pola rekrutmen caleg ini adalah pintu masuk untuk membenahi kinerja legsilatif secara kelembagaan, pada semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Faktanya, banyaknya kasus hukum dan etika yang melilit para wakil rakyat menjadi sinyal bahwa parpol wajib membenahi pola rekrutmen caleg tersebut. Di kanal youtube KPK, pada tanggal 5 November 2020 silam, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga Mei 2020, sebanyak 274 anggota DPR dan DPRD, berstatus sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh KPK.
Hasil analisa menyebutkan, pola rekrutmen caleg pada Pemilu 2019 ini juga terbilang tidak membaik. Parpol dengan sengaja membuka diri untuk dibajak oleh pihak yang berkehendak menjadi caleg. Ini akibat kaderisiasi mereka yang gagal. Terlebih jika caleg dimaksud memiliki usmber daya yang memaksa parpol untuk mendekatinya. Sumber daya itu yang utama adalah uang dan popularitas.
Banyaknya pengusaha dan selebritas yang menjadi caleg adalah bukti nyata dari indikasi tersebut. Popularitas dimiliki para selebritas yang terbiasa mendapatkan ruang berita di media massa. Uang dan akses biasanya menjadi alat nego para pengusaha yang kerap berminat nyaleg untuk proteksi bisnis mereka. Sesungguhnya yang membuat publik pesimistis bukan pada latar belakang profesi mereka, karena sesungguhnya setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih yang melekat pada dirinya. Semua orang dengan beragam latar belakang profesinya harus dihormati saat berminat untuk berpartisipasi dalam pencalegan.
Yang patut diberi catatan kritis sesungguhnya ialah model dadakan dalam pencalegan. Menjadi wakil rakyat itu amanah kekuasaan yang sangat serius. Jabatan tersebut tak layak dipegang sejumlah orang yang sedang belajar, coba-coba, atau sekadar berpetualang. Perlu kesungguhan dalam penyiapan diri sebelum mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Menjadi caleg bukan lahan mencari pekerjaan, karena substansi jabatan itu untuk dedikasi dan pengabdian mewakili sejumlah basis konstituen. Setiap caleg yang diajukan partai seharusnya memiliki kompetensi intelektual, moral, dan sosial. Partai seharusnya bukan semata mendistribusikan orang, melainkan memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, menyamakan nilai-nilai dan ideologi partai, serta melihat rekam jejak setiap caleg mereka. Tahapan penyiapannya tak cukup asal-asalan. Butuh sebuah sistem berjenjang dan berkelanjutan untuk mengumpulkan sejumlah nama yang benar-benar layak.
Memang, ketika parpol menyerahkan daftar calon ementara (DCS) kepada KPU, ada mekanisme tanggapan masyarakat. Namun, jarang sekali ditemukan, akibat tanggapan masyarakat dimaksud, parpol kemudian mengganti seorang caleg. Namanya ada pada DCS, kemudian diganti pada daftar calon tetap (DCT). Yang terjadi, ruang tanggapan masyarakat itu, digunakan oleh kompetitor untuk melaporkan lawan politiknya.
Kiranya, sebelum benar-benar menjadi DCS, parpol mengundang sejumlah elemen warga untuk berdiskusi, sekaligus meminta masukan. Hal itu dilakukan dua kali pada setiap dapil. Kemudian hasil diskusi itu, dibawa terlebih dahulu ke para akademisi, tokoh masyarakat, cendikiawan, jurnalis, dan pemuka agama, juga untuk diberi catatan. Baru kemudian mereka yang telah lolos dua tahap seleksi itu, dimajukan ke survei popularitas dan elektabilitas oleh lembaga tertentu. Hanya dengan cara itu, masyarakat dapat mengintip seleksi caleg. Disebut mengintip, bukan melihat, karena pada akhirnya, keputusan parpol mengenai pencalegan harus dapat diterima oleh semua warga. Tentu ada pertimbangan lain dari setiap parpol kenapa si Fulan misalkan ditetapkan sebagai caleg. Idelanya, pertimbangan utamanya adalah ideologi, bukan isi tas.
Karena jika isi tas yang menjadi parameter utama memilih seorang caleg, maka benar apa yang menjadi analisa Jeffrey A Winters. Bahwa, pasca lengsernya Soeharto tahun 1998, Indonesia justru bergerak ke arah oligarki penguasa kolektif yang tak berfungsi dengan baik, yang terorganisasi sebagai suatu demokrasi elektoral, dimana pelaku yang bisa mendominasi panggung politik hanyalah oligark yang memiliki kekayaan pribadi yang besar, dan elit yang mampu menarik atau mengambil sumber daya negara cukup besar. Hasilnya adalah demokrasi kriminal dimana para oligark yang tak terjinakkan bersaing dalam politik melalui pemilu. (***)
![]()